 |
| Memandang keadaan alam (Imogiri) |
Hutan merupakan sumber daya alam
yang tidak ternilai karena didalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai
sumber ekonomi, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air,
pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk
kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya.
Karena itu pemanfaatan hutan dan perlindungannya telah diatur dalam UUD 45, UU
No. 5 tahun 1990, UU No 23 tahun 1997, UU No. 41 tahun 1999, PP No 28 tahun
1985 dan beberapa keputusan Menteri
Kehutanan serta beberapa keputusan
Dirjen PHPA, Dirjen Pengusahaan Hutan dan peraturan daerah khusus propinsi
papua No 21 tahun 2008. Namun gangguan terhadap sumberdaya hutan terus
berlangsung bahkan intensitasnya makin meningkat.
Kerusahkan hutan dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga
hutan-hutan di propinsi Papua mengalami kerusakan fatal. Kerusakan
hutan di papua secara cepat atau lambat mengakibatkan dari tiga jalur
yang besar diantaranya: pertama, Penebangan Pohon secara liar (illegal loging)
maupun penebangan yang telah diijinkan oleh pemerintah (legal); seperti
penebangan kayu-kayu hutan adat orang Asmat di Papua bagian selatan yang
dikelola oleh perusahaan HPH PT Artika Optima Inti yang dinilai tidak adil.
Mengapa dinilai tidak adil? Pertama, upah penebangan kayu sebesar Rp. 7.500;
(tuju ribu lima ratus rupiah) per meter kubik itu dinilai terlalu renda
dibandingkan beratnya beban kerja penduduk; kedua, harga kayu Rp. 200; (dua
ratus rupiah) permeter kubik juga dianggap tidak adil bagi para pemilik kayu
yang sekaligus merupakan pekerja penebang tersebut, (Maria Rita Ruwiastuti,
2000: h, 18) dalam bukunya “Sesat Pikir” Politik Hukum Agraria. kedua,
Pembuangan limba perusahaan yang tidak memperhatikan kehidupan masyarakat
setempat maupun tumbuhan serta habitatnya; dan yang ketiga, penambangan
emas yang tidak memperhatikan hak-hak rakyat setempat hingga korban atas
kekayaannya sendiri, seperti PT Freeport dan penambangan liar di Degeuwo kabupaten
Paniai yang hamper setiap tahun terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM
Mengapa Terjadi
Konflik Pertambangan
Ibarat gunung es yang mulai memuntahkan lavanya,
intensitas kasus pertambangan meningkat dari tahun ketahun baik secara kualitas
maupun kuantitas. Konflik-konflik seperti ini bukanlah sesuatu yang baru di
Indonesia, tetapi telah terakumulasi sejak masa orde baru. Mulai konflik tanah,
buruh, pencemaran lingkungan, hingga pelanggaran HAM. (Siti Maimunah, 2012:
hal, 24) dalam bukunya Negara Tambang dan Masyarakat Adat, beberapa penyebab
mendasar konflik tersebut adalah: pertama, salah urus terhadap pengelolahan
bahan tambang yang hanya dipandang sebagai komoditas penghasil devisa dan
PAD semata. Sehingga seluruh upaya diarahkan untuk bagaimana mengeluarkan ijin
sebanyak-banyak dan melakukan pengerukan sebesar-besarnya. Banyak konflik
social dipicu oleh tumpang tindi peruntukan dan fungsi lahan. Misalnya kawasan
lindung dan wilatah kelolah masyarakat adat tumpang tindi dengan kawasan
pertambangan. Kedua, pengingkaran hak rakyat atas penguasaan dan pengelolaan
tanah. Tak ada satu pun kontra karya pertambangan dan kuasa pertambangan atau
ijin yang mendapatkan persetujuan rakyat sebelum diberikan. Bahkan kontrak
karya PT Freeport menyebutkan kawasan pertambangannya sebagai kawasan tidak
berpenghuni. Padahal kawasan tersebut adalah wilayah kelola suku pegunungan
tengah papua. Dalam UU No 11 tahun 1967 tentang Pertambangan Umum terdapat satu
klausul yang mewajibakan penduduk local menyerahkan tanahnya jika ada
pertambangan masuk. Akibatnya pilihan bagi penduduk hanya ada dua:
menerima ganti rugi sepihak, atau digusur karena menolak menerima ganti rugi.
Ketiga, daya rusak sector pertambangan yang tak mampu dikelola oleh perusahaan
dan Negara. Untuk mendapatkan 1 gram emas dibuang setidaknya 750 kg limbah
lumpur tailing yang mengandung logam berat dan 1730 kg limbah batuan. Jadi 1
gram emas menghasilkan limbah 2480 ribu kali berat produk yang dihasilkan. Tak
hanya itu, lubang-lubang menganga dengan dalam ratusan meter dan puluhan hektar
akan menjadi warisan jangka panjang penduduk local. Kemana limbah dengan jumlah
masiv ini dibuang? Ke lingkungan sekitar, ke lokasi-lokasi produktif tempat
mata pencaharian penduduk bernama sungai, hutan, rawa tropis, lahan pertanian
hingga laut.
Pemerintah dan
Perusahaan Bekerja Sama “Memelihara” Konflik ?
Meningkatnya konflik-konflik yang terjadi disektor
pertambangan karena tak perna mendapatkan penyelesaian yang memadai. Data Pokja
PA PSDA menunjukkan sekitar tahun 2002 terdapat sekitar 143 konflik
pertambangan. Hanya ada dua cara yang dilakukan dan perusahaan dalam meredam
konflik social disekitar wilayah pertambangan. (Siti Maimunah, 2012: hal, 26),
dalam bukunya (Negara Tambang dan Masyarakat Adat: Pertama, pendekatan keamanan
selalu dipakai oleh pemerintah dan perusahaan tambang dalam meredam protes
rakyat terhadap perusahaan tambang. Terlihat pada kasus pendudukan lokasi
pertambangan PT IMK di Kalteng tahun1999, kasus penembakan petani
dan nelayan yang memblokade PT Unocal tahun 2001, kasus aksi damai petani dan
nelayan yang menduduki lokasi tambang Newcrest di Maluku Utara tahun 2004, dan
banyak yang lainnya. Pemerintah telah memilih berhadapan dengan rakyat
dan melakukan pendekatan keamanan sebagai pilihan utama dibanding memikirkan
langkah-langkah cerdas dan berani untuk memenuhi tuntutan rakyatnya. Jika
banyak protes dilakukan penduduk local karena tanahnya diambil alih, bagi
pemiskinan atau lingkungannya tercemar limbah tambang maka mereka akan
disebut sebagai “pengganggu objek vital negara”. Atau jika ada tuntutan
pembagian hasil lebih adil melalui renegosiasi Kontrak Karya maka disebutlah
sebagai “tak ada kepastian hokum bagi investasi” hingga “investasi terancam
pergi” yang sangat menghina akal sehat adalah saat protes dan aksi rakyat yang
menuntut keadilan dituduh tidak lagi murni tetapi direkayasa oleh pihak lain.
Hal ini terlihat jelas dari pernyataan-pernyataan para petinggi militer dan
cabinet SBY JK yang menangggapi aksi serentak rakyat Papua dibeberapa lokasi
yang menuntut PT Freeport ditutup hingga terjadi bentrok berdara di Abepura
tanggal 18 Maret 2006. Mereka seolah ingin menyatakan bahwa orang Papua bodoh
sehingga tidak bisa membedakan mana yang provokasi dan mana yang upaya menuntut
ketidakadilan. Atau orang Papua tak akan menutut keadilan jika
dikompromi dari luar. Para pengurus negeri ini melupakan sejara dan fakta bahwa
operasi pertambangan Freeport telah melahirkan pelanggaran HAM, perusakan
lingkungan yang massif dan juga pemiskinan rakyat sekitar.
Kedua, selain pendekatan keamanan, upaya lain yang
belakangan ini dipilih adalah Community Development. (CD). Dengan cara ini
perusahaan dan pemerintah berharap masyarakat disibukkan dengan menerima,
mengelola, bahkan memperebut dana CD. Sehingga tak lagi mengingat ketidakadilan
yang mereka rasakan, kualitas lingkungan dan kesehatan yang makin parah hingga
waktunya perusahaan pergi dari lokasi tersebut. Program CD Unocal berhasil
memeca belah rakyat yang semula gigih memperjuangkan pencemaran 400ha sawa padi
di Rapaklama. Pemberian dana CD 1% dari hasil kotor PT Freeport membuat
kelompok-kelompok yang dulunya kritis menjadi sibuk memantau bagaimana dana CD
dihabiskan. Bahkan terjadi perang suku, suami istri berkelahi satu sama lain.
Konflik pertambangan adalah potret buruk pengelolaan sector tambang Indonesia.
Rakyat tak bisa terus dibodohi. Meningkatnya konflik-konflik pertambangan
dibanyak tempat adalah proses panjang rakyat belajar dan menyadari fakta-fakta
bahwa salah urus sector pertambangan merugikan lingkungan dan penghidupan
masyarakat. Negara harus segera melakukan kalkulasi manfaat (benefit) dan
mudhorot (cost) industry keruk ini dan mengubah arah pengelolaannya untuk
kebutuhan mendesak dan kepentingan antar generasi. Termasuk melakukan
penyelesaian konflik sebagai mandate yang harus dilakukan Negara dan perusahaan
tambang. Sudah hamper empat decade pengerukan kekayaan tambang kita, dan terus
berlangsung tanpa kita tahu berapa cadangan tersisa. Sementara kerusakan
lingkungan, pemiskinan, dan pelanggaran HAM di sekitar lokasi tambang terus
berlangsung. Surat kabar Dow Jones memberitakan penghasilan PT Freeport
meningkat lebih dua kali lipat diakhir tahun 2005.
Sementara Indonesia terus terpuruk utang,
pontang-panting mengemis bantuan pengamanan bencana dan terus melakukan
pemotongan subsidi-subsidi rakyatnya untuk kesehatan, pendidikan, pangan, air
dan energy (listrik, BBM)(Jakarta, 22 Maret 2006)
Perspektif
Masyarakat Lokal Terhadap Hutan Papua
Di lihat dari kondisi alam papua, Belakangan ini menjadi ancaman serius bagi
kelangsungan dan keselamatan hidup bagi masyarakat yang bermukim di sekitarnya
maupun pada umumnya. Ancaman terbesar di Papua pada saat tertentu secara
tidak sadar akan terjadi: pertama, banjir, longsor sebuah contoh besar
yang kita bisa lihat adalah banjir Wasior yang telah menelan beberapa nyawa
orang serta fasilitas yang ada akibat penebangan hutan yang di lakukan oleh
oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ; dan yang kedua, lahan
pertanian masyarakat local papua akan di tempati oleh migrasi sehingga dalam
kehidupan masyarakat akan terjadi sebuah masalah dalam hal ekonomi.
Kemudian dari pada itu, hutan memiliki fungsi ekonomi bagi masyarakat
papua bukan hanya fungsi ekologis. Hutan memberikan banyak kekayaan yang bisa
di manfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Oleh karena
itu, keberadaan hutan di papua harus pahami baik-baik pemerintah
kepenjangan tangan dari pusat (Jakarta) yang mengeksploitasi kekayaan alam
papua yang tanpa memperhatikan keberadaan penduduk local papua yang
kehidupannya masih tergantung pada hutan itu.
Keberadaan
hutan papua sebagai ibu yang memberikan makanan kepada penduduk local papua,
maka pemerintah jangan anggap hutang sebagai sumber pendapatan yang
mendatangkan uang yang berlipat, jika uang tersebut digunakan
untuk membangun papua serta memberdayakan masyarakat tidak mengapa, tetapi di
gunakan untuk kepentingan pribadi alias Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN)
hal demikian inilah yang telah mengorbankan serta membawa persoalan dalam
kehidupan masyarakat local papua.
Pengolahan hutan yang di lakukan oleh masyarakat local dengan cara-cara
tradisional di dasari atas keseimbangan kebutuhan mereka sehingga
pelestarian alam tetap terjaga. Namun, setelah adanya Otonomi Khusus
(otsus), industrialisasi serta pemekaran telah bergeser pengolaan
pemanfaatan pola tradisional. Kapitalis dengan pengolahan hutan telah
mendapat dukungan dari Negara maupun daerah berdampak secara luas
seperti: ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi.
Secara
Ekologis
Dengan adanya Kapitalis akan berdampak kerusakan hutan papua karena ia
tidak memperhatikan pelestarian hutan sebagai sumber kehidupan bagi
masyarakat local papua, melainkan hanya mengeksploitasi untuk mencari dan
mendapatkan keuntungan yang berlipat sehingga disuatu saat akan terjadi bencana
alam, seperti banjir dan longsor.
Sosial Budaya
Di lihat dari Aspek sosial budaya, yang jelas pengolahan pemanfaatan hutan yang
di lakukan oleh kapitalis akan berdampak pada masyarakat local papua yang
selama ini kehidupan mereka tergantung pada hutan akan tersingkir oleh migrasi.
Dengan adanya dukungan dari Negara maupun daerah kapitalis akan merusak
hutan papua yang sebelumnya berfungsi sebagai sember ekonomi bagi masyarakat,
akhirnya hutan-hutan tersebut akan ditempati oleh migrasi.
Aspek Ekonomi
Di lihat dari aspek ekonomi, kapitalis akan merusak hutan tanpa memperhatikan
pelestariannya. Namun, untuk lebih menguntungkan pada kapitalis itu
sendiri serta elit-elit politik local yang kepanjangan tangan dari jakarta.
Hutan papua adalah sumber kehidupan masyarakat local papua, sehingga
dengan masuknya kapitalis telah merusak hutan sehingga yang menjadi
korban masyarakat local papua dalam hal ekonomi.
Pemekaran
Aspek yang paling mencolok mengenai proses
desentralisasi sungguh tidak terencana. Pemekaran merupakan istilah Indonesia
untuk menyebut subdivisi distrik-distrik dan propinsi yang ada dalam rangka
menciptakan unit-unit administrasi yang baru. Pemekaran seperti itu juga
terjadi dinegara-negara lain. Di Amerika Serikat, pemekaran seperti itu disebut
redistricting, yaitu pembentukan kembali distrik-distrik, dan menyangkut
politik pemilihan. Di beberapa Negara di Eropa Timur setelah era Soviet
berakhir, tujuannya adalah melepaskan penyatuan paksa dari era Soviet dan
kembali ke unit-unit semula yang lebih kecil (Illner 2000; Majcherkiewicz 200).
Baik di Amerika Serikat maupun Eropa Timur proses ini tidak
controversial. Tetapi di Afrika ia sama-sama politisnya dengan Indonesia.
Di Negeria jumlah distrik pemerintahan local bertambah menjadi dua kali lipat
selama tahun 1980-an sebagai akibat dari dorongan desentralisasi yang rakus dan
penuh konflik. Para elit terus-menerus mendesak pusat untuk menciptakan satuan
pemerintah lokal, sambil mengorupsi dana pembangunan lokal. Demikian juga
presiden Museveni di Uganda dipaksa untuk melipat-duakan jumlah distrik selama
masa pemerintahannya, meskipun para pakar berpendapat distrik tersebut terlalu
mahal dan tidak perlu. Di Indonesia pun, pergerakan primordial yang
mementingkan daerah lokal menuntut wilayah administrasi baru atas dasar argument
argument sejarah yang sering kali tidak jelas. Tujuan sebenarnya adalah
menambah jabatan di birokrasi. Kami tetap menggunakan istilah bahasa Indonesia
“pemekaran” yang secara harafiah berarti “mekarnya bungu”. Jelasnya, istilah
ini sebenarnya merupakan sesuatu yang “salah kapra” karena gerakan
ini tidak mengarah keluar dank e atas melainkan justru kedalam kea rah dirinya
sendiri dalam bentuk subdivisi yang terus terjadi tanpa henti. Istilah yang
mungkin lebih tepat “involusi administratif”, sesuai pemikiran Greetz tentang
involusi pertanian ketika begitu banyak orang sama-sama butuh menggarap
sejengkal tanah yang sama. Pemekaran mencerminkan kemampuan yang sama melakukan
improvisasi di saat-saat yang sulit.
Para pembuat kebijakan yang telah mendapat pelatihan
di luar negeri dan menulis tentang desentralisasi legislative di Indonesia
tidak bermaksud memicu terjadinya pemekaran yang tergesa-gesa (Turner et al.
2003). Terdapat kepustakaan yang luas tentang desentralisasi diseluruh dunia
mengenai transfer kekuatan dari suatu tingkat administrasi ke yang
lainnya, tetapi kepustakaan tersebut tidak perna menyebut perlunya menggariskan
kembali batas-batas wilayah administratif itu sendiri. Namun itulah yang justru
terjadi di Indonesia. Dalam kurun waktu beberapa tahunsaja jumlah provinsi
bertambah dari 27 buah menjadi 33 sementara jumlah distrik yang ada
(kadang-kadang disebut daerah tingkat dua atau kabupaten) meningkat hamper 50%
hingga 440.
Pemekaran yang terjadi setelah tahun 1998 secara umum
dipicu dari bawah. Meskipun para pejabat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
menyangkal bahwa pemekaran sering tidak perlu dilakukan dan sangat mahal, namun
berkali-kali para politisi setempat berhasil untuk memaksakannya agar bisa
mengusulkan provinsi dan distrik yang baru. Para politisi setempat biasanya
melakukan pendekatan dengan pihak pusat di Jakarta tapi tentu saja tidak
melalui birokrasi langsung namun lewat DPR, yang kemudian menerbitkan
undang-undang yang memerintahkan pembentukan unit-unit baru. Untuk memperkuat argument
mereka bahwa pemekaran akan lebih “mendekatkan pemerintah dengan
rakyatnya”, mereka diam-diam menyogok uang dalam jumlah yang sangat
besar. Masing-masing distrik baru akan berubah menjadi sebua bonanza bagi para
kontraktor bangunan karena distrik-distrik baru harus dilengkapi dengan
sederetan kantor-kantor baru. Pihak militer dan politi tentu saja
mendukung pemekaran ini karena struktur komando territorial mereka juga akan
segera diperbarui mengikuti perubahan itu.
Kombinasi dua proses yang pada dasarnya
berbeda-desentralisasi administrative dan demokratisasi popular-membuahkan
kompetisi yang begitu bebas antara para elit lokal dalam upaya mengendalikan
Negara. Mereka sering melakukan kompetisi seperti itu dalam tataran
etnis. Bagi masing-masing faksi, sebuah distrik dijadikan
alas an melakukan kompetisi. Pemekaran karenanya merupakan suatu studi
kasus untuk menjawab pertanyaan “mengapa pembentukan provinsi begitu bersifat
etnis sementara kondisi Negara lemah?” pemekaran yang begitu tergesa-gesa
mirip dengan yang terjadi pada tahun 1950-an, ketika kekuasaan formal Jakarta
juga menjadi semakin lemah karena pergolakan antarfaksi dipusat serta
pemberontakan bersenjata di provinsi-provinsi. Pusat akhirnya merespon
pergolakan itu dengan menciptakan delapan provinsi baru. Meski begitu akan
sangat keliru beranggapan semua itu merupakan suatu kemenangan
kekuatan-kekuatan sentrifugal. Dibalik semangatnya gerakan identitas lokal
tidak ada keinginan untuk melepaskan diri, namun justru untuk menyingkirkan
lawan lokal dengan membuktikan diri lebih loyal lagi kepada Jakarta, yang
bagaimanapun masih merupakan sumber uang tunai. Memang Jakarta pada tahun
1950-an menawarkan provinsi-provinsi baru sebagai imbalan bagi para loyalis
karena mereka telah menyingkirkan kaum separatis (Klinken 2006), (Nordholt
Schulte Henk and Klinken van Gerry, 2007: h, 25),dalam bukunya: Renegotiating
Boundaries; Local Politics in Post-Suharto Indonesia, yang diterjemakan dalam
bahasa indonesia pada Yayasan Obor Indonesia.
Pemekaran
Merusak Hutan Papua
Ketika ada pemekaran yang di mekarkan oleh pemerintah Pusat orang akan
menyambut dengan baik tanpa melihat maksud dan tujuannya dari pada
pemekaran tersebut. Semua orang telah mengetahui bahwa maksud dan tujuan dari
pemekaran adalah untuk membangun daerah tersebut. Namun, dilihat dari
perkembangannya untuk kepentingan oknum-oknum tertentu sehingga
atas dukungan mereka capitalis masuk untuk merusak hutan dengan alasan
untuk membangun daerah tersebut. Dilihat dari realitasnya,
Pemekaran-pemekaran baik Provinsi maupun kabupaten khususnya di papua mudah di
respon oleh pemerintah pusat (Jakarta) sehingga papua pada umumnya
pada saat ini kita bisa katakan satu suku tiga atau empat
kabupaten contohnya adalah suku MEE yang terbagi ke dalam beberapa
kabupaten seperti: Paniai, Dogiyai dan Deiyai, dan beberapa tahun kedepan
kemungkinan akan terjadi satu keluarga satu kabupaten, sungguh pemekaran
ini memisahkan kami yang dulu bersatu. Pemekaran ini menjambatani sehingga para
kapitalis masuk dengan mudah untuk mengeksploitasi hutan atas dukungan
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah demi kepentingan mereka sendiri.
Dalam hal ini untuk mengoksploitasi hutan yang ada tanpa melihat kehidupan
masyarakat local yang kehidupannya selalu tergantung dari pada hutan itu
sendiri.
Pemekaran-pemekaran yang di mekarkan bukan untuk membangun serta memberdayakan
masyarakat dalam hal Ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial melainkan untuk
kepentingan Jakarta dan elit-elit politik local untuk memanfaatkan kekayaan
alam papua, sehingga kehidupan masyarakat berada dibawa garis kemiskinan
atas kekayaannya sendiri.
Oleh karena itu, kami mengimbau kepada pemerintah daerah provinsi Papua mulai
hari ini juga semua pemekaran baik provinsi maupun kabupaten harus berhenti,
karena melalui pemekaran itu merusak hutan-hutan di papua serta telah
mangorbankan masyarakat papua, seperti yang telah terjadi konflik antara
pendukung kandidat satu dengan kandidat yang lain di kabupaten puncak
yang telah menelan nyawa sebanyak 40an orang pada tanggal 19 juli 2011
hingga masih belum selesai sampai masuk pada tahun 2012. Pemerintah Provinsi
papua serta masyarakat juga harus sadar bahwa pemekaran bukan membawa
kesejahteraan dan membangun papua tetapi, untuk kepentingan oknum-oknum
tertentu, dan membawa bencana diantara masyarakat.
Kemudian daripada itu, pemerintah juga harus mengambil kebijakan yang jelas
untuk menutup penebangan pohon seperti yang di kabupaten nabire distrik
wanggar, penambangan liar seperti di Degeuwo kabupaten paniai yang hampir
setiap tahun menelan korban nyawa manusia, dan juga yang di pertengahan jalan
trans Nabire Paniai tepatnya di kilo meter 64, yang di lakukan dengan
seenaknya.
Thomas Hobbes mengatakan (homo ets homini lopus), artinya manusia adalah
serigala dari manusia yang lain, artinya manusia ingin menguasai atau berkuasa
atas orang lain tanpa memperhatikan hak dan kewajiban orang lain,
melakukan tindakan sewenang-wenangnya atas orang lain. Pada hal setiap
orang mempunyai hak yang tidak boleh di ganggu gugat oleh siapa pun, sama
hal yang sedang terjadi di papua yang mana hak hak masyarakat dirampas oleh orang-orang
yang ingin menguasai bumi cendrawasih itu.
Pengalaman adalah guru yang baik demikian tutur orang bijak, alangka banyaknya
segudang pengalaman yang di miliki oleh bumi cendrawasih ini, sehingga apabila
kita tidak melihat serta belajar dari pengalaman yang sudah ada,
maka bencana alam pada saat tertentu akan terjadi lagi pula beberapa tahun
kedepan kehidupan orang asli papua dan juga pulau papua itu sendiri akan
menjadi pulau jawa yang kedua. Untuk itu, pemerintah yang kaki tangan
pusat (Jakarta) harus sadar jangan pikir kepuasan sesaat saja. Namun,
hutan papua perlu di lestarikan demi kehidupan anak cucu kita kedepan maupun
tetap terjaganya dari bahaya bencana alam yang mengorbankan masyarakat lokal
papua.
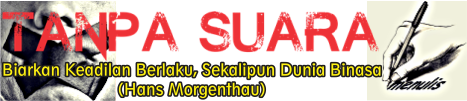








Tidak ada komentar: